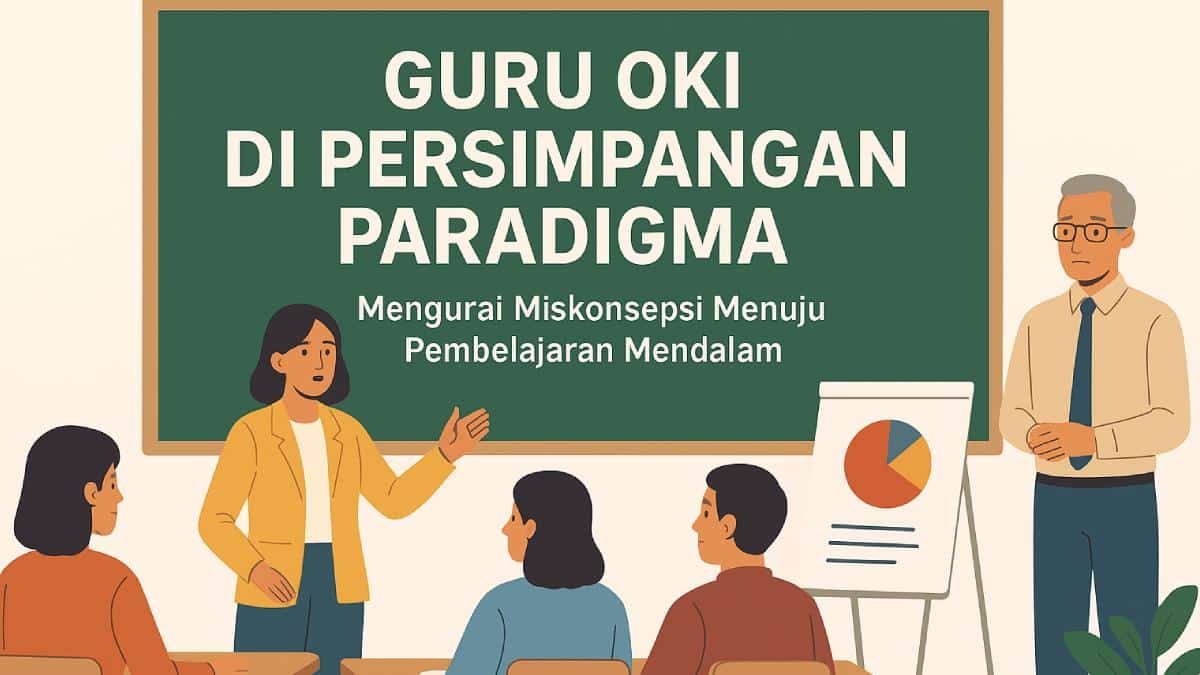DI ENAM sekolah rujukan, mulai dari SDN 1 Muara Baru hingga SMAN 3 Kayuagung, sejumlah guru dan kepala sekolah perwakilan dari berbagai jenjang pendidikan, dari PAUD hingga SMK, duduk merapatkan barisan. Mereka adalah representasi dari ratusan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang tengah mengikuti Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM) yang difasilitasi oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatera Selatan.
Perhelatan ini, didanai penuh oleh BOS Kinerja, menandai bukan sekadar transfer ilmu, melainkan sebuah pertaruhan besar pendidikan di daerah dalam merespons agenda transformasi nasional. Tujuan utamanya adalah merombak praktik pedagogi guru dari sekadar mentransfer pengetahuan permukaan (surface learning) menjadi memandu murid mengaitkan materi dengan makna hidup, yaitu Pembelajaran Mendalam (deep learning).
Namun, transisi filosofis dan praktis ini ternyata tidak mulus. Di balik semangat adaptasi, guru-guru di OKI dihadapkan pada sejumlah miskonsepsi filosofis dan pedagogis yang krusial. Analisis mendalam dari para pakar yang menjadi narasumber utama dalam pelatihan ini, terekam dalam materi yang dipaparkan, menunjukkan adanya jurang yang lebar antara tujuan ideal yang digariskan kebijakan baru dengan implementasi di ruang kelas.
Kebijakan Baru: Menjawab Kebutuhan Kompetensi Lulusan
Lulusan Landasan utama pergerakan ini terangkum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Regulasi yang menggantikan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 ini mempertegas bahwa kompetensi lulusan harus dicapai melalui pembelajaran yang transformatif, berfokus pada pengembangan minat dan bakat murid, serta disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Secara ringkas, kerangka ini menuntut kurikulum dirancang untuk melahirkan lulusan yang siap menjadi pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) dan agen perubahan (agent of change).
Yuli Rahmawati, Ph.D., salah seorang Tim Pengembang Pembelajaran Mendalam, menegaskan bahwa PM adalah kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yang semuanya berpusat pada murid. Pilar ini berawal dari Delapan Dimensi Profil Lulusan yang ingin dicapai, meliputi Keimanan dan Ketakwaan, Kewargaan, Kreativitas, Penalaran Kritis, Kolaborasi, Kemandirian, Kesehatan, dan Komunikasi. Delapan dimensi ini, menurut Yuli Rahmawati, harus menjadi lensa utama dalam merancang setiap kegiatan belajar, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari hafalan fakta, melainkan dari sejauh mana murid mampu mengaplikasikannya dalam memecahkan masalah kompleks yang relevan.
Dimensi-dimensi ini disokong oleh Tiga Prinsip Pembelajaran yang harus menjadi karakter pembeda PM, yaitu: pembelajaran harus Berkesadaran (Mindful) yang melibatkan refleksi dan regulasi diri; Bermakna (Meaningful) yang mengaitkan topik dengan konteks kehidupan nyata; serta Menggembirakan (Joyful) yang menumbuhkan rasa dihargai dan bangga akan penyelesaian tantangan.
Tiga Jebakan Miskonsepsi yang Menjerat Guru
Transisi paradigma ini, meskipun didasari niat baik, ternyata rentan terhadap penyederhanaan makna yang menyesatkan. Triska Fauziah R., S.Pd., seorang guru yang memaparkan praktik PM di tingkat Sekolah Dasar, secara lugas memaparkan tiga miskonsepsi paling umum yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi guru dan fasilitator di OKI.
Pertama, keyakinan bahwa surface learning tidak diperlukan lagi. Banyak guru yang menganggap PM berarti harus langsung melompat ke tahapan penalaran kritis atau kreativitas, seolah-olah penguasaan fakta dasar bisa diabaikan. Triska Fauziah membantah pandangan ini, menekankan bahwa pembelajaran permukaan (surface learning) yang berada pada tahap uni-struktural dalam Taksonomi SOLO, adalah fondasi yang esensial menuju pemahaman mendalam.
“Guru perlu memberi kesempatan murid mengenali fakta dasar, misalnya mengenali jenis kegiatan ekonomi, sebelum masuk ke tahap analisis dan refleksi. PM adalah perjalanan berjenjang, bukan lompatan,” ujarnya. Tanpa fondasi fakta yang kuat, murid tidak akan memiliki kerangka berpikir yang kokoh saat menganalisis masalah yang lebih kompleks.
Kedua, penafsiran bahwa belajar menggembirakan identik dengan ice breaking atau hiburan. Prinsip pembelajaran ‘menggembirakan’ seringkali direduksi menjadi kewajiban mengisi kelas dengan tepuk tangan atau permainan.
Triska Fauziah menegaskan bahwa ini adalah penyederhanaan yang keliru. Yang membuat belajar menggembirakan sesungguhnya adalah pengalaman murid merasa dihargai, diakui, dan berhasil menyelesaikan tantangan belajar yang terukur. Rasa bangga dan kepemilikan atas proses dan hasil inilah yang memicu motivasi internal murid untuk menjadi pembelajar sejati, bukan sekadar respons terhadap stimulus hiburan sesaat.
Ketiga, miskonsepsi yang mereduksi refleksi hanya sebagai penulisan ringkasan pelajaran. Dalam PM, refleksi adalah jembatan yang menghubungkan pengetahuan dengan penerapannya, dan harus melampaui tugas klerikal “tulis apa yang kamu pelajari.”
Triska menjelaskan bahwa refleksi harus mencakup Refleksi Diri (murid menganalisis cara mereka belajar dan strategi yang berhasil) dan Refleksi Konten (murid menarik makna dari pengalaman belajar, mengaitkannya dengan kehidupan yang lebih luas, dan merumuskan cara regulasi diri di masa depan). Refleksi inilah yang melatih dimensi Berkesadaran dan Kemandirian murid.
Praktik Pedagogik: Mengubah Kelas Menjadi ‘Ruang Negosiasi’
Untuk menanggulangi miskonsepsi tersebut, pelatihan di OKI membedah Empat Kerangka Pembelajaran yang harus mengubah tata laksana kelas, sebagaimana disoroti dalam materi yang dikembangkan dari Prof. Suyanto, Ph.D. dan Yuli Rahmawati, Ph.D. Kerangka ini mencakup Praktik Pedagogis, Kemitraan Pembelajaran, Lingkungan Pembelajaran, dan Pemanfaatan Digital.
Dalam ranah Praktik Pedagogis, guru dituntut menerapkan strategi yang berfokus pada pengalaman langsung, seperti pembelajaran inkuiri, belajar melalui proyek, simulasi Role Play, dan wawancara. Model ini menuntut guru tidak lagi menjadi penceramah, melainkan seorang aktivator dan kolaborator.
Triska Fauziah menjabarkan bagaimana implementasi di Sekolah Dasar dapat dilakukan melalui tema sederhana, misalnya “Kegiatan Ekonomi di Lingkungan Sekitar.” Prosesnya dibagi menjadi lima sesi yang bersifat hierarkis, dimulai dengan penguasaan fakta dasar melalui video, dilanjutkan dengan fase aplikasi kontekstual.
Pada fase krusial ini, murid tidak sekadar menghafal, tetapi terlibat dalam Role Play sebagai pelaku ekonomi dan bahkan melakukan wawancara langsung (atau digital) dengan pelaku usaha di sekitar sekolah.
“Fase aplikasi kontekstual inilah yang melatih Dimensi Kolaborasi dan Komunikasi mereka. Kelas diubah menjadi ruang interaktif, seperti ‘toko mini’ untuk simulasi, yang menumbuhkan rasa bangga dan kebermaknaan,” jelas Triska, menegaskan bahwa perubahan praktik ini memerlukan Lingkungan Pembelajaran yang mendukung interaksi.
Selain itu, PM secara eksplisit mendorong Kemitraan Pembelajaran yang melibatkan seluruh ekosistem: antar murid, murid dengan guru, murid dengan orang tua, dan murid dengan pelaku usaha. Keterlibatan ini, khususnya dengan komunitas luar sekolah, menjadikan materi yang dipelajari memiliki konteks nyata dan tidak terisolasi dalam buku teks.
Fleksibilitas Administrasi dan Transformasi Asesmen
Perombakan di OKI ini juga didukung oleh relaksasi administrasi. Materi Kebijakan Kurikulum yang merujuk pada Permendikbudristek 10/2025 mempertegas bahwa perencanaan pembelajaran dibagi dalam dua ruang lingkup: satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas.
Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan. Dalam dokumen resmi, disebutkan bahwa guru cukup melampirkan beberapa contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran.
Ini adalah langkah nyata untuk memangkas birokrasi dan memungkinkan guru lebih fokus pada PM yang luwes dan adaptif terhadap perkembangan minat murid.
Tantangan besar berikutnya adalah Asesmen. Prof. Suyanto, Ph.D., dalam kerangka materinya, menekankan bahwa PM menuntut asesmen bergeser dari mengukur daya ingat menuju mengukur tingkat kedalaman pemahaman.
Kerangka PM menggunakan Taksonomi SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome), yang membagi pemahaman menjadi empat tahap: Uni-struktural (fakta tunggal), Multi-struktural (banyak fakta yang belum terhubung), Relasional (fakta terhubung menjadi konsep), dan Extended Abstract (mampu menggeneralisasi dan merefleksi konsep di konteks baru).
Asesmen kini difokuskan pada kemampuan guru dalam bertanya (checking understanding) yang efektif untuk menstimulasi keterampilan berpikir peserta didik dan mengidentifikasi pada tahap SOLO mana murid berada. Dengan demikian, asesmen menjadi alat diagnosis untuk memandu diferensiasi, bukan sekadar alat evaluasi akhir.
Komitmen dan Realitas Lapangan
Keterlibatan 8 fasilitator untuk Kepala Sekolah dan 19 fasilitator untuk Guru (total 27 tenaga ahli), yang tersebar di jenjang PAUD hingga SMK, menunjukkan bahwa transformasi PM ini dipandang sebagai ekosistem, bukan proyek parsial.
Kepala sekolah didorong untuk menjadi Pimpinan Pembelajaran yang memastikan Kreativitas dan Fleksibilitas yang diberikan sebagai ruang inovasi dan bukan menjadi sumber hambatan birokrasi baru. Mereka memegang peran kunci dalam memastikan ekosistem pendidikan sekolah mendukung praktik pedagogik mendalam.
Namun, semangat perubahan ini harus berhadapan dengan realitas infrastruktur di daerah. Meskipun program ini didanai BOS Kinerja untuk mendorong adopsi teknologi, kesenjangan sarana prasarana masih menjadi ganjalan terbesar.
“Meskipun semangatnya besar, tantangan di lapangan tetap terasa nyata. Kami harus akui, tidak semua sekolah di OKI, terutama yang di pelosok, memiliki akses internet stabil atau perangkat digital yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis eksplorasi yang dituntut PM,” ujar Lutiem Purwaningsih, Kepala SDN 1 Burnai Timur, saat ditemui di sela-sela pelatihan.
Luti sapaan akrabnya melanjutkan, tantangan tidak hanya bersumber dari fasilitas fisik, tetapi juga alokasi waktu. “Guru dituntut adaptif, tapi beban administrasi dan tuntutan kurikulum lama kadang masih menghimpit. Kami butuh dukungan yang konsisten, bukan hanya pelatihan sekali jalan. PM ini menuntut perubahan pola pikir, dan itu butuh waktu serta sumber daya,” tegasnya.
Pernyataan Lutiem Purwaningsih ini menjadi cermin bahwa kompleksitas Pendidikan Indonesia, seperti yang diakui Yuli Rahmawati, Ph.D., menuntut upaya multidimensi: membangun pemahaman konsep guru, meningkatkan kemampuan asesmen, dan yang tak kalah penting, menjembatani kesenjangan infrastruktur agar prinsip Pemanfaatan Digital dalam PM dapat terwujud secara merata.
Guru-guru di OKI kini memikul tanggung jawab untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh di enam sekolah rujukan tersebut menjadi praktik nyata di ruang kelas. Peran mereka telah bergeser drastis: dari penyampai materi menjadi pemandu perjalanan makna.
Perjalanan panjang menuju Pembelajaran Mendalam dan mewujudkan dimensi profil lulusan yang tangguh, adaptif, dan siap menjadi agen perubahan, baru saja dimulai di OKI. Keberlanjutan inisiatif yang didanai BOS Kinerja ini akan menjadi tolok ukur komitmen daerah di Sumatera Selatan dalam memprioritaskan kualitas pendidikan.
(dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.